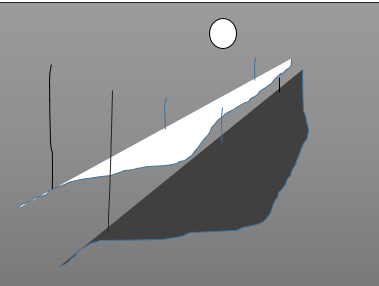Miskin, Ah, kata itu terlalu sering saya dengar. Terasa pecah di telinga. Ingin rasanya menghapus kata itu dari kamus bahasa. Kata yang seharusnya tak pantas ada. Menghinakan, mendzolimi, memvonis, tendensius dan segala sumpah serapah bergelombang di hati saya saat pagi berkabut.
Hari itu memang terasa pengap. Debu-debu berterbangan tertiup angin kecil. Debu-debu itu menari-nari lalu menclok di tubuh si kakek. Sosok manusia tua yang sering saya lihat di perempatan jalan itu. Bajunya lusuh, topinya kumal, duduk di trotoar memacari lalu lalang kendaraan.
Pengemiskah kakek itu? Tadinya saya kira benar. Tapi, kakek itu tak pernah mengedahkan telapak tangannya seperti pengemis lazimnya. Juga tak ada rantang di depannya atau apapun seperti layaknya seorang pengemis. Kakek itu hanya duduk-duduk saja meski memang penampilannya kaya pengemis. Entahlah apa yang dilakukan ia, saya tak mengerti.
“Kakek ngapain disini?” saya bertanya sebab tak mau lagi memikirkan dia. Tapi, kakek hanya tersenyum, tak menjawab.
“Kakek darimana?” kali ini saya menyodorkan sebatang rokok, lalu diambil oleh si kakek dan disulutnya. Asapnya tak begitu bergulung-gulung. Kakek itu tampak kesusahan mengisap rokoknya, giginya yang kemong tak kuat lagi menyedot asap rokok.
Saya duduk disebelahnya. Membiarkan orang-orang lewat melihatkan kami. Ingin mengorek isi hati si kakek, siapa dia dan ngapain selalu ada ditrotoar itu setiap hari. Makanya, saya terus bertanya, namun hanya satu atau dua kalimat yang kakek katakan, itu pun sulit saya dengar sesulit kakek menjawab.
“Seharusnya kakek tidak disini setiap hari. Tak baik untuk kesehatan. Debu-debu dan asap knalpot itu nempel dibadan kakek dan jadi penyakit, nanti kakek sakit,”
Kakek hanya menatap wajah saya sekilas. Lalu, pandangannya tetap ke arah lalu lalang kendaraan.
“Rumah kakek dimana?”
Telunjuk kakek yang sedikit bengkok menunjuk ke arah yang entah dimana. Tanpa bicara.
“Kenapa selalu disini?”
Kakek yang tersenyum, tanpa berkata-kata. Senyum yang biasa terlihat dari bibir kemong kakek-kakek.
“Kalau kakek tak punya rumah, ayo ikut saya saja,”
Kakek menggelengkan kepalanya. Tapi kali ini dia bicara: “nggak usah, kakek masih punya rumah,” ujarnya.
‘Ya sudah syukur kalau begitu.
“Kakek mau makan?” Tanpa menunggu jawaban, nasi bungkus dapat beli di warung Mbak Yul diserahkan ke kakek dan ia lahap menyantapnya. Selesai lalu minum air mineral. Terlihat agak segar wajah kakek.
Satu jam disana, saya pamit meninggalkan kakek. Ingin rasanya terus mendampingi kakek. Ada rasa nyaman duduk disana. Tapi, untuk apa. Miskin tidak harus duduk di trotoiar dengan baju compang camping, seperti kakek itu. Saya pun bangkit meninggalkan kakek.
***
Hari terus berganti. Tapi kata miskin masih terngiang-ngiang di telinga. Ingin rasanya menghapus kata itu di kamus bahasa. Kata yang tendensius. Kata yang menghinakan si kakek, setidaknya dari bibir saya sendiri. ‘Ya kakek itu jelas orang miskin jika dilihat dari penampilannya.
Kakek itu tak pernah bangun tidur minum susu dan roti. Saya yakin begitu. Itu untuk kakek kaya yang tiap pagi duduk-duduk di kursi goyang menanti anak atau cucunya ngajak bicara tentang harta kekayaan dan perusahaan miliknya yang sudah diserahkan kepada turunnya.
Kakek kaya beda keriput wajahnya. Putih bersih, terjamin, meski kalau mati sama saja dengan kakek miskin, dikubur, dan hari itu, kakek yang selalu duduk di trotoar masih terlihat ada disitu. Setiap hari saya melihatnya dan setiap hari pula saya menemaninya duduk duduk.
Kakek semakin lancar bicaranya. Bercerita banyak tentang kehidupannya, masa lalunya dan saat ini. Saya pun jadi tahu siapa dia. Ngeri rasanya, dugaan saya benar kakek itu miskin. Padahal, katanya dia pejuang pernah berperang melawan tentara jepang.
Lupa-lupa ingat, kakek bercerita kisah heroiknya di medan pertempuran, dan tak membuat saya tertarik dengan ceritanya itu. Kronologisnya terlalu sama dengan cerita veteran lain. Berperang pakai bambu runcing dan banyak yang gugur diberondong peluru musuh. Itu-itu saja plotnya. Bosan.
Tapi ada satu cerita si kakek yang menbuat saya tertarik lalu ingin terus mendengarkannya. Kisah cintanya justru. Usai Jepang pulang ke negerinya dan Indonesia merdeka, kakek muda menjalin asmara dengan seorang sinden wayang golek. Ia cantik, kata si kakek. Kebayang, batasan kecantikan sinden jaman itu.
Kakek sangat mencintainya. Tapi sinden itu tak mau diajak nikah. Ia malah berpaling dinikahi juragan beras di kampungnya. Kakek muda kalangkabut, hatinya terluka dan ia pergi ke sebuah gunung untuk bertapa. Kakek merenung disana. Rasa cintanya telah membuat dia jadi seseorang yang aneh. Kakek perdalam ilmu kebatinan dari gurunya di gunung itu. Hingga akhirnya kakek menjadi seorang jawara. Tak hanya silat, ia juga sakti untuk membuat orang bertekuk lutut. Entah ilmu apa namanya.
Bertahun-tahun kakek hidup bersama gurunya di gunung itu. Hingga hari yang ditentukan, ia pun turun gunung. Masuk keluar kampung mencari cintanya yang kandas. Karena kesaktian itulah, pacarnya yang dulu, sinden yang dinikahi bandar beras itu, menemuinya, menangis minta dinikahi.
Katanya, ia tak bahagia meski bergelimang harta. Ingatannya hanya tertuju pada kakek meski pemuda miskin. Bahagia ternyata tidak harus kaya. Begitu kata si sinden yang diceritakan kakek saat kami bicara berduaan. Tapi miskin tetap penghinaan, kata saya kepada kakek.
Lalu? Kakek berkisah, ia bawa kabur sinden itu. Mengurai kisah cinta seperti dulu. Kakek banyak tersenyum saat itu. Ia menang dalam pergulatan asmara. Perempuan yang ia sayangi berada dalam pelukannya. Perempuan yang meninggalkan suami dan tiga anaknya.
Tentu saja, kakek dan sinden itu jadi buronan orang sekampung. Dicari kemana-mana tak juga ditemukan. Ilmu sakti kakek telah menggelapkan pelacakan orang-orang. Kakek dan sinden tak juga ditemukan. Mereka pun hidup bahagia berumahtangga bertahun-tahun meski miskin.
Hingga diakhir bicaranya, kakek menyebut ia baru sebulan keluar dari penjara. Belasan tahun meringkuk dibalik jeruji besi seusai mencekik sinden cantik karena sering menghinakan kakek dengan sebut kata miskin.***